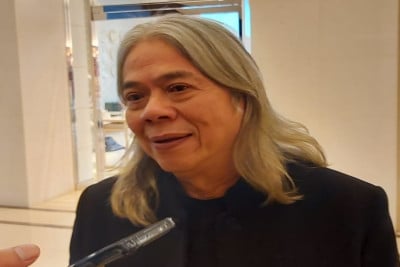Bisnis.com, JAKARTA—Aturan pembatasan lalu lintas bernama three-in-one di Jakarta atau satu kendaraan minimal berpenumpang, sudah tamat. Kini yang berlaku adalah sistem nomor polisi ganjil-genap.
Konsep 3-in-1 memang selalu menarik dibicarakan. Sebagai contoh, apa jadinya bila keragaman (diversity), tanggung sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), dan pemasaran aneka budaya (multicultural marketing) dilebur menjadi sebuah strategi pemasaran baru yang diharapkan lebih mampu menjawab tantangan global?
Sepintas mungkin agak sulit menemukan titik temu yang ‘pas’ dari ketiga hal tersebut. Apalagi bila tujuan akhirnya adalah untuk menjawab secara lebih komprehensif masalah pemasaran dewasa ini.
Sejumlah pertanyaan relevan bisa diajukan, misalnya mengapa harus berujung ke pemasaran? Mengapa tidak untuk memberdayakan keberagaman atau mengefektifkan implementasi CSR di lapangan?
Menjawab pertanyaan tersebut sebenarnya mudah saja. Apabila bisa menjawab atau memberikan solusi untuk tiga masalah sekaligus (3-in-1), lalu mengapa harus berdiri sendiri-sendiri (one by one)?
Wacana ‘kolaborasi’ (aligning) antara keragaman, CSR, dan pemasaran aneka budaya tetap menjadi topik hangat di dunia manajemen.
Saking serunya arus besar itu dibahas, Stephen Palacios, executive vice president Cheskin Added Value, mengakuinya sebagai sebuah emerging market reality (Stephen Palacios, Aligning diversity, CSR and multicultural marketing, 2008).
Pemicunya tidak lain adalah kondisi pasar yang makin dinamis seiring dengan kian ketatnya kompetisi global dan menguatnya tuntutan terhadap akuntabilitas serta transparansi korporasi.
Dinamika Pasar
Palacios mempunyai keyakinan bahwa perusahaan yang piawai ‘mengawinkan’ ketiga aspek tersebut akan jauh lebih bernilai ketimbang mereka yang cuek terhadap dinamika pasar.
Nah, wajah dunia pemasaran AS sebenarnya sudah berubah sejak tahun 2000 ketika data sensus menunjukkan bahwa diam-diam populasi minoritas, yaitu Hispanic dan warga kulit hitam, terus bertambah. Kini, 30% dari warga AS adalah mewakili kedua populasi tersebut.
Yang menarik, selain populasinya bertambah, kemampuan daya beli mereka juga menguat dan diperkirakan meningkat pesat di masa mendatang.
Banyak perusahaan di AS yang tidak terlalu serius menaggapi hasil sensus tersebut. Kalaupun ada yang sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan baru itu, tidak sedikit pula yang justru reaksioner.
Padahal yang justru perlu segera dilakukan adalah membangun ‘kompetensi budaya’ (cultural competence) untuk menangkap peluang pasar yang sudah di depan mata tersebut.
Alih-alih korporasi, pihak pertama yang bergerak adalah Merrill Lynch karena memandang hasil sensus itu sebagai peluang baru. Institusi keuangan global tersebut kemudian membuat semacam pengembangan bisnis aneka budaya (multicultural business development).
Seperti menangkap dinamika pasar yang tengah berubah, CEO General Electric Jeff Immelt pernah menyebutkan dalam artikelnya di International Herald Tribune, “saya ini seorang penjual. Saya paham betul bahwa Anda tidak bisa menjual barang untuk waktu lama kecuali bila Anda sendiri adalah bagian dari budaya dari barang yang dijual.”
Begitu pula dengan unsur CSR-nya. CSR bukan sekadar good will tetapi harus menjadi bukti nyata yang dirasakan manfaatnya secara luas.
Apabila kedai kopi Starbucks bisa menerapkan CSR tidak hanya sebagai fair trade dan memperlakukan para pemasok secara eco friendly, mengapa Anda sebagai pemimpin korporasi tidak melakukan strategi serupa?
Cetak Biru
Kisah sukses (best practise) bertebaran di dunia. Anda tinggal mencomot cetak birunya saja.
Ketika Indra Nooyi terpilih sebagai CEO Pepsi Co pada 2006, gebrakan pertamanya adalah mencanangkan semangat tempur baru dibawah ‘mantera’ Performance with Purpose, sebuah filosofi untuk membangun brand yang dipercaya pasar dan bukan sekadar mengeruk keuntungan.
Hasilnya adalah perusahaan tersebut membuat meniman kesehatan seperti NAKED Juice, Aquafina, dan air mineral Propel yang bisa diterima konsumen dari berbagai latar belakang budaya.
Bisa belajar pula dari Lisa Quiroz, eksponen Time Warner Inc. Selama lima tahun dia melakukan restrukturisasi CSR lewat program People en Espanol, dari 1998 sampai 2004.
Quiroz merasa lebih berdaya untuk mengkoordinasikan aset perusahaan secara lebih strategik untuk menjawab berbagai isu. “Kami lebih tertarik mencari bakat-bakat baru lewat proyek Time Warner Storytellers daripada menggelar konser musik di taman.”
Time Warner tidak berhenti sampai di situ. Manajemen melibatkan enam divisi yaitu HBO, Time Warner Cable, Turner Broadcast, Time Inc, AOL, dan Warner Brothers) untuk secara bersama-sama memainkan irama CSR dalam keberagaman dalam proyek tahunan bertajuk Diversity Action Plan.
Sudahkah kalangan dunia usaha di Tanah Air menyelami hasil sensus seperti yang dilakukan korporasi global? Rasanya belum.
Apalagi untuk dikembangkan lebih lanjut menuju penyatuan keberagaman, CSR, dan pemasaran aneka budaya.
Masing-masing masih asyik berjalan sendiri. Mereka belum bergandengan tangan untuk mempersembahkan ‘orkestra’ yang apik. Menggempur tapi menghibur.